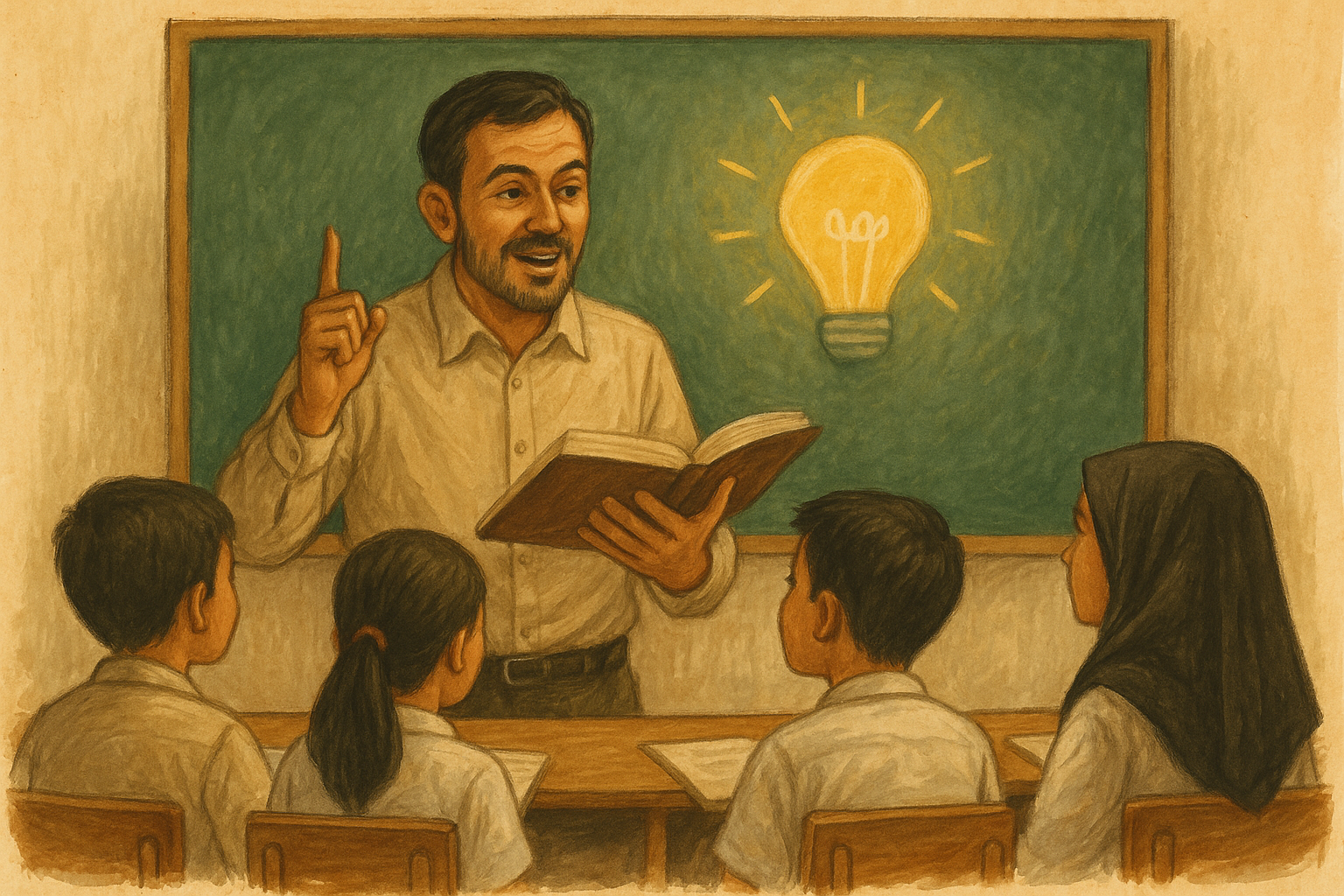Hari ini, seorang anak usia tujuh tahun bisa lebih cepat mencari video kartun kesukaannya di YouTube dibandingkan ayahnya yang sedang belajar buka Google Drive. Ia tak perlu diajari cara menyambungkan WiFi, atau membuka TikTok, karena dunia digital adalah rumah mainnya. Di sisi lain, orang tua gelisah: apakah anak-anak ini sedang beradaptasi dengan zaman, atau justru sedang digiring masuk ke dalam lorong gelap teknologi yang tak sepenuhnya dipahami?
Itulah dilema besar kita saat ini. Digitalisasi anak, aman atau ancaman?
Mari kita bicara apa adanya. Teknologi digital bukan setan. Ia juga bukan malaikat. Ia adalah alat. Netral. Sama seperti pisau dapur. Di tangan ibu, jadi alat memotong sayur. Di tangan perampok, bisa menjadi alat kejahatan. Internet dan gawai pun begitu. Ia bisa membuat anak belajar cepat, menemukan ide kreatif, atau bahkan jadi ahli coding sejak SD. Tapi di saat yang sama, ia bisa membuka akses ke kekerasan, pornografi, penipuan, dan perundungan siber yang mengerikan.
Di titik inilah, orang tua dan masyarakat punya tanggung jawab besar. Kita tak bisa menyalahkan teknologi lalu berharap zaman berhenti bergerak. Yang harus kita lakukan adalah belajar, mengimbangi, dan membimbing.
Sayangnya, banyak orang tua justru kalah duluan. Anak baru usia delapan tahun sudah punya Instagram, TikTok, dan akun game online. Orang tuanya masih bingung bedakan reels dan stories. Bahkan lebih parah, gawai diberikan sebagai pengasuh digital agar anak diam di rumah. Maka kita temukan pemandangan menyedihkan: satu keluarga duduk dalam satu meja makan, tapi masing-masing sibuk dengan dunia dalam layar.
Ini bukan soal menolak digitalisasi, tapi soal bagaimana anak dibekali untuk menghadapinya. Bukan dengan larangan semata, tapi dengan literasi digital yang memadai. Anak perlu diajak berdialog, didampingi, dan diawasi. Seperti halnya kita mengajari anak menyebrang jalan dengan hati-hati, kita juga harus mengajari mereka berselancar di dunia digital dengan etika dan kesadaran.
Pemerintah sebenarnya sudah memulai langkah, seperti dengan program Internet Sehat, kurikulum TIK di sekolah, atau kerja sama dengan Kominfo dan BSSN untuk meningkatkan keamanan digital. Tapi tentu saja, ini belum cukup. Literasi digital harus tumbuh dari rumah. Dari percakapan-percakapan sederhana antara ayah, ibu, dan anak soal apa yang mereka lihat hari ini di dunia maya.
Kita juga perlu mengedukasi guru dan sekolah agar tidak hanya mengajarkan matematika dan IPA, tapi juga nilai-nilai kebajikan di dunia digital. Anak-anak harus tahu bahwa tidak semua yang viral itu baik. Bahwa membully orang di kolom komentar adalah kekerasan. Bahwa menyebar hoaks bisa membahayakan nyawa.
Jadi, digitalisasi pada anak, apakah aman atau ancaman? Jawabannya bergantung pada kita, orang dewasa. Jika kita memilih cuek dan menyerahkan anak pada dunia maya, maka digitalisasi akan menjadi ancaman yang pelan-pelan menghancurkan generasi. Tapi jika kita hadir, mendampingi, dan mengarahkan, maka digitalisasi bisa menjadi jalan emas untuk melahirkan anak-anak hebat di masa depan.
Mari berhenti membiarkan gawai membesarkan anak-anak kita. Mari kita yang membesarkan mereka, dengan cinta, logika, dan literasi.
Tidak semua yang instan itu baik. Anak yang tumbuh dengan bimbingan digital yang sehat akan jadi pemimpin masa depan yang bijak, bukan sekadar seleb TikTok viral dua menit yang hilang ditelan algoritma. (#)